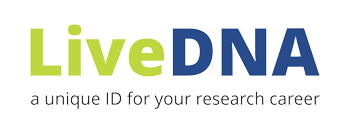By. Tabrani. ZA
Kajian tentang sumber ilmu dalam filsafat adalah masuk dalam rumpun epistemologi. Dalam perjalanan sejarah pemikiran manusia, kajian tentang epistemologi telah dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Dalam dunia Islam, pembahasan tentang epistemologi ilmu sudah dilakukan sejak masa al-Kindi (796-873 M). Secara khusus, kajian tentang epistemologi ini dilakukan dalam kajian filsafat ilmu.(1)
Dalam kajian epistemologi di Barat, pembahasan tentang sumber ilmu melahirkan tiga mazhab utama, yaitu rasionalisme, empirisme dan fenomenalisme Kant.(2) Keberatan Islam terhadap ketiga mazhab ini sebagaimana akan ditunjukkan nanti, terutama karena pengingkarannya terhadap wahyu sebagai objek ilmu pengetahuan. Dalam Islam, kajian terhadap sumber ilmu memadukan bahan-bahan empirikal (kealaman) dan spiritual (kewahyuan). Pemaduan kedua bahan inilah yang akan memunculkan konsep epistemologi Islam yang berbeda dengan konsep epistemologi Barat. Konsep tentang sumber ilmu selanjutnya akan berimplikasi terhadap perumusan isi kurikulum dalam pendidikan Islam. Sebagaimana disinggung di atas, kajian yang pokok tentang Devine Science (sumber ilmu) diwakili oleh tiga mazhab utama, yaitu rasionalisme, empirisme dan fenomenalisme Kant. Berikut dijelaskan ketiga mazhab dimaksud, baru kemudian akan menjelaskan pandangan Islam tentang sumber pengetahuan sebagai berikut:
a) Rasionalisme
Mazhab ini berasal dari para filosof Eropa seperti Rene Descartes (1596-1650) dan Immanuel Kant (1724-1804), dan lain-lain yang populer disebut sebagai teori rasional.(2) Menurut teori ini ada dua sumber bagi pengetahuan (konsepsi). Pertama, penginderaan (sensasi). Menurut teori ini, konsepsi manusia tentang panas, cahaya, rasa dan suara karena penginderaan terhadap hal-hal itu. Kedua, adalah fitrah, dalam arti bahwa akal manusia memiliki pengertian-pengertian dan konsepsi-konsepsi yang tidak muncul dari indera, tetapi ia sudah ada dalam lubuk fitrah. Dalam pengertian yang terakhir ini, jiwa menggali gagasan-gagasan tertentu dari dirinya sendiri. Rene Descartes berpandangan konsepsi-konsepsi fitri ini adalah ide “tuhan”, jiwa, perluasan dan gerak serta pemikiran-pemikiran yang mirip dengan semuanya itu dan bersifat sangat jelas dalam akal manusia. Tetapi bagi Kant, semua pengetahuan manusia adalah fitri, termasuk dua bentuk ruang dan waktu serta duabelas kategori Kant.(4)
Menurut mazhab ini, indera adalah sumber pemahaman terhadap konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan sederhana. Hanya saja indera bukan satu-satunya sumber. Di samping indera, ada fitrah yang mendorong munculnya sekumpulan konsepsi pada akal.
Baqir Ash-Shadr pada teori rasionalis mengatakan bahwa:
Konsepsi manusia tidak mendapatkan alasan munculnya sejumlah gagasan dari indera, karena memang ia bukan konsepsi-konsepsi inderawi, maka harus digali secara esensial dari lubuk jiwa, dari sini jelas bahwa motif filosofis bagi perumusan pada teori rasional akan hilang sama sekali, jika dapat menjelaskan secara meyakinkan konsepsi mental, tanpa perlu mengandalkan gagasan fitrah.(5)
Selanjutnya menurut Harun Nasution pada teori Descartes bahwa:
Secara metodologi ilmu pengetahuan harus mengikuti jejak ilmu pasti, meskipun ilmu pasti bukanlah metode ilmu yang sebenarnya. Ilmu pasti hanya boleh dipandang sebagai penerapan yang paling jelas dari metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri lebih umum. Segala konsepsi dan gagasan baru bernilai benar jika secara metodologi dikembangkan dari intuisi yang murni (fitrah).(6)
Lebih lanjut Harun Nasution menuturkan, teori Descartes dipengaruhi oleh berbagai pertentangan pemikiran filsafat pada zamannya. Pertentangan ini menyebabkan ia bersikap meragukan segala sesuatu. Dalam konteks ini hanya ada satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu bahwa aku ragu-ragu (aku meragukan segala sesuatu). Sifat meragukan ini bukan khayalan, melainkan suatu kenyataan. Aku ragu-ragu, atau aku berpikir, dan oleh karena aku berpikir maka aku ada (cogito ergo sum). Memang menurut teori Descartes, apa saja yang dipikirkan bisa saja merupakan suatu khayalan, akan tetapi bahwa kegiatan berpikir bukanlah khayalan. Dalam hal ini “tiada seorangpun yang dapat menipu saya, bahwa saya berpikir, dan oleh karena itu di dalam hal berpikir ini saya tidak ragu-ragu, maka aku berada”.(7)
b) Empirisme
Istilah empirik berasal dari kata Yunani emperia, yang berarti pengalaman inderawi. Kaum empiris telah memberi tekanan kepada empirik (pengalaman), baik pengalaman lahiriah maupun batiniah sebagai sumber pengetahuan. Dengan demikian, empirisme bertentangan dengan rasionalisme. Di antara tokohnya adalah Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).(8)
Teori ini berpendapat bahwa penginderaanlah satu-satunya yang membekali akal manusia dengan berbagai konsepsi dan gagasan, dan bahwa potensi mental akal budi adalah potensi yang tercermin dalam berbagai persepsi inderawi. Jadi ketika manusia mengindera sesuatu, ia akan dapat memiliki suatu konsepsi tentangnya, yakni menangkap form dari sesuatu itu dalam akal budi. Adapun tentang gagasan-gagasan yang tidak terjangkau oleh indera, menurut aliran ini, tidaklah dapat diciptakan oleh jiwa, demikian pula jiwa tidak dapat membangunnya secara esensial dalam bentuk yang berdiri sendiri.(9) Akal budi berdasarkan teori ini, hanyalah berfungsi mengelola konsepsi dan gagasan inderawi. Hal itu dilakukan dengan cara menyusun konsepsi-konsepsi dan membagi-baginya.
Baqir Ash-Shadr mengatakan bahwa:
Mengonsepsikan “sebungkah gunung emas” atau membagi-bagi “pohon” kepada potongan-potongan dan bagian-bagian atau dengan abstraksi dan universalisasi, misalnya dengan memisahkan sifat-sifat dari bentuk itu, dan mengabstraksikan bentuk itu dari sifat-sifatnya yang tertentu agar darinya akal dapat membentuk suatu gagasan universal. Hal ini dapat dicontohkan dengan upaya mengkonsepsikan Zayd, dan mengurungkan setiap kekhasan yang membedakannya dari ‘Umar. Dengan proses substraksi (pengurangan) ini, akal menyarikan suatu gagasan abstrak yang berlaku, baik atas Zayd maupun ‘Umar.(10)
Senada dengan Baqir Ash-Shadr selanjutnya Harun Nasution pada teori Thomas Hobbes mengatakan bahwa, aliran empirisme di Inggris pada abad ke-17 telah membangun suatu sistem filsafat yang lengkap mengenai “yang ada” secara mekanis, yang menjadi pijakan dasar filsafat empirisme. Ia adalah seorang materialis pertama dalam filsafat modern.(11)
Lebih lanjut menurut Harun Nasution, segala yang ada bersifat bendawi. Bendawi dimaksudkan ialah segala sesuatu yang tidak bergantung kepada gagasan kita. Ia juga mengajarkan bahwa segala kejadian adalah gerak, yang berlangsung karena keharusan. Realitas segala yang bersifat bendawi terliput di dalam gerak itu. Segala obyektifitas di dalam dunia luar bersandar kepada suatu proses tanpa pendukung yang berdiri sendiri. Ruang atau keluasan tidak memiliki eksistensi atau keber-“ada”-an sendiri. Ruang justru gagasan tentang hal yang ber-“ada” itu. Sedangkan waktu adalah gagasan tentang gerak.(12)
Konsistensi gagasannya juga terlihat dalam pandangannya tentang manusia. Ia memandang manusia tidak lebih dari pada suatu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi pada manusia dapat dijelaskan sebagaimana kejadian alamiah bendawi lainnya secara mekanis. Jiwa itu sendiri menurutnya adalah kompleks dari proses-proses mekanis dalam tubuh. Akal bukanlah pembawaan, melainkan hasil perkembangan karena kerajinan.
Seperti di singgung di atas, pengenalan atau pengetahuan diperoleh karena pengalaman. Pengalaman adalah awal segala pengetahuan. Pengenalan dengan akal hanya memiliki fungsi mekanis, karena pengenalan dengan akal pada hakikatnya mewujudkan suatu proses penjumlahan dan pengurangan. Pengenalan dengan akal dimulai dengan pemakaian kata-kata (pengertian-pengertian), yang hanya mewujudkan tanda-tanda menurut adat-kebiasaan saja, dan yang menjadikan jiwa manusia dapat memiliki gambaran yang diucapkan dengan kata-kata itu. Selanjutnya, hal ini akan membentuk pengalaman (empirik). Isi pengalaman itu adalah keseluruhan atau totalitas segala pengamatan yang disimpan di dalam ingatan dan digabungkan dengan suatu pengharapan masa depan, sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lampau.(13)
c) Fenomenalisme Kant
Filsuf Jerman abad ke-18 Immanuel Kant melakukan pendekatan kembali terhadap masalah hakikat rasio dan indera sebagai sumber pengetahuan setelah memperhatikan kritikan-kritikan yang dilancarkan oleh David Hume terhadap sudut pandang yang bersifat empiris dan rasional. Mengapa pendirian Kant disebut sebagai fenomenalisme. Kant berpendapat bahwa sebab akibat tidak dapat dialami. Marilah kita memperhatikan pernyataan, “kuman tipus dapat menyebabkan demam tipus.” Bagaimanakah kita sampai dapat mengetahui keadaan yang mempunyai hubungan sebab-akibat ini. Kebanyakan orang akan mengatakan, “setelah diselidiki para ilmuan diketahui bahwa bila ada orang yang menderita demam tipus, tentu terdapat kuman tersebut, dan bila kuman ini tidak terdapat di dalam diri seseorang, maka orang itu tidak menderita deman tipus.(14)
Dari penjelasan di atas dengan jelas terlihat bahwa syarat “adanya kuman tipus” dan “demam tipus” mesti ada sebelum disimpulkan bahwa kuman tersebut menyebabkan demam. Karena boleh jadi “seorang yang dalam dirinya ada kuman tipus” tapi tidak menderita demam. Bagaimanapun, pengamatan mengungkapkan kepada kita tentang kuman tersebut dan juga tentang orang yang sehat atau yang sakit. Tetapi pengamatan, betapapun juga banyaknya tidak dapat menunjukkan kepada kita kuman yang menyebabkan penyakit tersebut. Bagaimanakah kita dapat memperoleh pengetahuan bahwa kuman itulah yang menyebabkan penyakit tersebut. Ditinjau dari sudut pandangan empiris, Hume menolak bahwa kita akan dapat mengetahui sebab akibat sebagai suatu hubungan yang bersifat niscaya. Jika melihat seekor kucing dan kemudian kita memukulnya, kita tidak dapat mengatakan bahwa kucing itulah yang menyebabkan kita memukulnya, meskipun kita lakukan berkali-kali. Dalam kedua peristiwa di atas tidak tampak hubungan sama sekali. Maka mengapakah kita bila melihat kuman dan kemudian melihat orang sakit, kita lalu mengatakan bahwa kuman itulah yang menyebabkan penyakit.
Indera hanya dapat memberikan data indera, data itu ialah warna, cita rasa, bau, rasa dan sebagainya. Memang benar, kita mempunyai pengalaman, tetapi sama benarnya juga bahwa untuk mempunyai pengetahuan (artinya menghubungkan hal-hal), maka kita harus keluar dari atau menembus pengalaman, kata Kant. Jika dalam memperoleh pengetahuan kita menembus pengalaman, maka jelaslah, dari suatu segi pengetahuan itu tidak diperoleh melalui pengalaman, melainkan ditambahkan pada pengalaman.
Jika orang tidak dapat membayangkan berupa apakah suatu “rasa yang bersahaja” dengan “suatu bunyi yang kasar”, maka jelaslah bahwa data indera yang murni tidaklah merupakan pengetahuan. Pengetahuan terjadi bila akal menghubungkan, untuk memperoleh fakta bahwa tekanan terhadap sesuatu menyebabkan terjadinya bunyi. Hubungan merupakan cara yang dipakai oleh akal untuk mengetahui suatu kejadian, hubungan itu tidak alami. Hubungan ialah bentuk pemahaman kita, dan bukan isi pengetahuan.(15)
Referensi
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). h. 107.
Louis O. Kattsof, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996) h. 142.
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali (Bandung: Mizan, 1993), h. 28.
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali, h 29
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali, h 30
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI- Press, tth) h. 20.
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam, h 21
Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 105
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali , h 32
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali, h 32
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam , h 32
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam, h 33
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam, h. 34.
Kattsof, Louis O. Pengantar Filsafat. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996).h 142
Kattsof, Louis O. Pengantar Filsafat, h. 143
Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). h. 107.
Louis O. Kattsof, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996) h. 142.
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali (Bandung: Mizan, 1993), h. 28.
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali, h 29
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali, h 30
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI- Press, tth) h. 20.
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam, h 21
Juhaya S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 105
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali , h 32
Muhammad Baqir Ash-Shadr, Falsafatuna. Terj. M. Nur Mufid bin Ali, h 32
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam , h 32
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam, h 33
Harun Nasution Akal dan Wahyu dalam Islam, h. 34.
Kattsof, Louis O. Pengantar Filsafat. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1996).h 142
Kattsof, Louis O. Pengantar Filsafat, h. 143
Sumber: http://bagusk1919.blogspot.co.id/2014/10/bab-iii-integrasi-islam-agama-dan.html