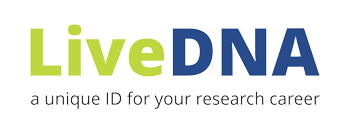By: Tabrani. ZA
Masa depan suatu
bangsa sangat tergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta
didiknya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat kita
wujudkan melalui pendidikan dalam keluarga, pendidikan masyarakat maupun
pendidikan sekolah.
Indonesia merupakan negara yang mutu
pendidikannya masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain bahkan
sesama anggota negara ASEAN pun kualitas SDM bangsa Indonesia masuk dalam
peringkat yang paling rendah. Hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara
maksimal. Indonesia sekarang menganut sistem pendidikan nasional. Namun, sistem
pendidikan nasional masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ketika dunia pendidikan kembali dituding
telah gagal membentuk watak mulia pada anak didik. Maka seperti biasa, segera
muncul saran untuk memperbaiki kurikulum atau muatan pada mata ajaran. Tapi,
bila sebelumnya yang dipersoalkan hanya sebatas masalah mata pelajaran atau
paling jauh struktur kurikulum, mungkin banyak dari kalangan pemerhati dan
pelaku pendidikan, mempersoalkan hal yang lebih mendasar. Yakni tentang sistem
pendidikan nasional yang ditudingnya masih mewarisi sistem pendidikan
kolonial.
Diakui atau tidak, sistem pendidikan yang
berjalan di Indonesia saat ini memang adalah sistem pendidikan yang
sekular-materialistik. Bila disebut bahwa sistem pendidikan nasional masih
mewarisi sistem pendidikan kolonial, maka watak sekuler-materialistik inilah
yang paling utama, yang tampak jelas pada hilangnya nilai-nilai transendental
pada semua proses pendidikan.
Sistem pendidikan semacam ini terbukti
telah gagal melahirkan manusia shaleh yang sekaligus mampu menjawab tantangan
perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Secara kelembagaan,
sekularisasi pendidikan menghasilkan dikotomi pendidikan yang sudah berjalan
puluhan tahun, yakni antara pendidikan “agama” di satu sisi dengan pendidikan
umum di sisi lain. Pendidikan agama melalui madrasah, institut agama dan
pesantren dikelola oleh Departemen Agama, sementara pendidikan umum melalui
sekolah dasar, sekolah menengah dan kejuruan serta perguruan tinggi umum
dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional.
Disadari atau tidak, berkembang penilaian
bahwa hasil pendidikan haruslah dapat mengembalikan investasi yang telah
ditanam. Pengembalian itu dapat berupa gelar kesarjanaan, jabatan, kekayaan
atau apapun yang setara dengan nilai materi yang telah dikeluarkan. Agama
ditempatkan pada posisi yang sangat individual. Nilai transendental dirasa
tidak patut atau tidak perlu dijadikan sebagai standar penilaian sikap dan
perbuatan. Tempatnya telah digantikan oleh etik yang pada faktanya bernilai
materi juga.
Pendidikan Sekuler bagian dari Kehidupan Sekuler
Sistem pendidikan yang
material-sekuleristik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari
sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekuler. Dalam sistem
sekuler, aturan-aturan, pandangan dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah
secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang
pendidikan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya
ditempatkan dalam urusan individu dengan tuhannya saja. Maka, di tengah-tengah
sistem sekularistik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari
nilai-nilai agama. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik
yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang
egoistik dan individualistik, sikap beragama yang sinkretistik
serta paradigma pendidikan yang materialistik.
Ilusi Dunia Pendidikan
Untuk menerapkan sistem pendidikan yang baik dan
mencerahkan bagi siswa, para guru, orang tua dan masyarakat, tak perlu
jauh-jauh berguru pada Paolo Friere dengan sistem pendidikan pembebasannya atau
Rabindranat Tagore dengan Santiniketannya, apalagi dengan meliberalkan sistem
pendidikan, cukup dengan menghilang perangkap “ilusi-nya” bahwa pemerintah,
orang tua dan guru yang lebih tahu apa yang terbaik bagi siswa. Nilai-nilai apa
yang pantas dan benar ditanamkan di benak para siswa yang kita pandang hanya
kelinci-kelinci percobaan, atau tanah liat yang bisa kita bentuk seenanknya dan
semaunya dengan tanpa melihat pada kekhususan-kekhususan dan anaeka potensi,
kreativitas, serta kemampuan yang berbeda dari tiap-tiap siswa.
Dewasa ini banyak orang yang menghabiskan waktunya
secara spartan di lembaga-lembaga pendidikan lalu merasa tidak mendapat apa-apa
dan menjadi apa-apa, Kendati telah meraih serenceng gelar yang berderet di
belakang namanya. Faktanya memang banyak orang-orang pintar jebolan sekolahan
yang merasa frustasi, tersesat dan akhirnya jadi koruptor. Belum lagi bicara
yang putus sekolah atau DO dari kampus lalu kemudian mengisi daftar panjang
para penganggur dan pemakai obat-obatan, serta peserta tawuran antar kampus
atau sekolah.
Walau banyak juga para alumni yang sukses dan
telah berada di jalan yang benar, tapi secara umum, pendidikan sekarang perlu
dijiwai dengan semangat baru, mungkin itulah sebabnya pemerintah bersikeras
mengimplementasikan kurikulum baru 2013, dengan visi dan misi yang lebih
menekankan pada pendidikan karakter siswa, meski masih kontroversi.
Kebanyakan para siswa telah melewatkan waktunya di
sekolah bertahun-tahun untuk tidak mendapat arti dan nilai hidup manusia dengan
pertolongan orang lain yang telah mengungkapkan pengalaman mereka lewat
pelajaran-pelajaran dan tulisan-tulisan mereka, tetapi kebanyakan mereka hanya
sibuk berusaha mengumpulkan kredit, naik kelas, lalu mendapat ijazah dan dengan
demikian mengorbankan perkembangan diri pribadi mereka sendiri.
Dalam suasana seperti itu, tidak mengherankan
bahwa orang menjadi semakin enggan untuk belajar karena perkembangan mental dan
emosional yang sesungguhnya telah dihalang-halangi oleh situasi pendidikan, di
mana murid menganggap guru lebih sebagai tuan yang selalu menuntut, bukan
sebagai pembimbing yang menemani mereka dalam mencari pengetahuan dan
pengertian.
Salah satu dari persoalan-persoalan yang paling
besar dalam pendidikan ialah diberikannya pemecahan masalah, sedangkan masalah
itu sendiri sebetulnya tidak ada. Agaknya sumber pendidikan dan pemberian
informasi yang paling sedikit digunakan ialah pengalaman murid sendiri.
Kadang-kadang guru berbicara mengenai kasih dan benci, takut dan kegembiraan,
harapan dan keputusasaan sementara murid mencatat atau melihat keluar jendela
karena bosan. Juga tak paham, karena sejatinya apa yang didengarkan bukan
pengalaman merek sendiri tentang hal-hal tersebut di atas. Dengan sendirinya
persoalan-persoalan yang muncul di sana takkan pernah dapat tertangani apalagi
tersolusikan kelak.
Mereka biasanya terima saja karena tak ingin
tampak ringkih dan bodoh. Tak ada yang berani mengingatkan pada teman-teman dan
guru bahwa masih ada beberapa soal yang sangat penting dalam kehidupan yang belum
disentuh. Mereka merasa lebih aman dengan diam saja tanpa protes pada yang
membuat mereka mengantuk, demi menghindar dari cap murid yang tak patuh dan
santun.
Maka mengajar, pertama-tama menuntut diciptakannya
suatu ruang di mana murid atau guru dapat masuk dalam suatu relasi yang tidak
diwarnai rasa takut dan menjadikan pengalaman hidup mereka masing-masing
sebagai sumber utama dan paling bernilai bagi perkembangan dan pendewasaan
pribadi. Untuk itu dituntut rasa “saling percaya” Di sana mereka yang mengajar
dan mereka yang ingin belajar dapat saling hadir satu bagi yang lain, tidak
sebagai pihak-pihak yang saling berlawanan, tetapi sebagai pribadi-pribadi yang
berjuang bersama dan mencari kebenaran yang sama pula.
Jadi pendidikan mengimplemantasikan bukan
sekedar pengajaran atau penyampaian pengetahuan (ta’lim), tetapi
pelatih, pembangkit seluruh potensi diri siswa (tarbiyah). Jadi guru
bukan sekedar seorang mu’alim atau penyampai pengetahuan, tetapi juga
sekaligus murabbi, pelatih jiwa dan kepribadian sekaligus pendamping
atau teman seperjalanan siswa.
Solusi Fundamental
Pendidikan yang materialistik adalah buah
dari kehidupan sekularistik yang terbukti telah gagal menghantarkan manusia
menjadi sosok pribadi yang utuh, yakni seorang Abidu al-Shalih yang
muslih. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, paradigma
pendidikan yang keliru di mana dalam sistem kehidupan sekuler, asas
penyelenggaraan pendidikan juga sekuler. Tujuan pendidikan yang ditetapkan juga
adalah buah dari paham sekularistik, yakni sekedar membentuk manusia-manusia
yang berpaham materialistik dan serba individualistik.
Kedua, kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksana
pendidikan, yakni (1) kelemahan pada lembaga pendidikan formal yang tercermin
dari kacaunya kurikulum serta tidak berfungsinya guru dan lingkungan
sekolah/kampus sebagai medium pendidikan sebagaimana mestinya, (2) kehidupan
keluarga yang tidak mendukung, dan (3) keadaan masyarakat yang tidak kondusif .
Tidak berfungsinya guru/dosen dan rusaknya
proses belajar mengajar tampak dari peran guru yang sekadar berfungsi sebagai
pengajar dalam proses transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge),
tidak sebagai pendidik yang berfungsi dalam transfer ilmu pengetahuan dan
kepribadian (transfer of personality), karena memang kepribadian
guru/dosen sendiri banyak tidak lagi pantas diteladani.
Lemahnya pengawasan terhadap pergaulan
anak dan minimnya teladan dari orang tua dalam sikap keseharian terhadap
anak-anaknya, makin memperparah terjadinya disfungsi rumah sebagai salah satu
unsur pelaksana pendidikan. Sementara itu, masyarakat yang semestinya menjadi
media pendidikan yang riil justru berperan sebaliknya akibat dari berkembangnya
sistem nilai sekuler yang tampak dari penataan semua aspek kehidupan baik di
bidang ekonomi, politik, termasuk tata pergaulan sehari-hari yang bebas dan tak
acuh pada norma agama; berita-berita pada media masa yang cenderung
mempropagandakan hal-hal negatif seperti pornografi dan kekerasan, serta
langkanya keteladanan pada masyarakat. Kelemahan pada unsur keluarga dan
masyarakat ini pada akhirnya lebih banyak menginjeksikan beragam pengaruh
negatif pada anak didik. Maka yang terjadi kemudian adalah sinergi pengaruh
negatif kepada pribadi anak didik.
Oleh karena itu, penyelesaian problem
pendidikan yang mendasar harus dilakukan pula secara fundamental, dan itu hanya
dapat diujudkan dengan Oleh karena itu, penyelesaian problem pendidikan yang
mendasar harus dilakukan pula secara fundamental, dan itu hanya dapat diujudkan
dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan
paradigma pendidikan sekuler menjadi paradigma Islam. Sementara pada tataran
derivatnya, kelemahan ketiga faktor di atas diselesaikan dengan cara
memperbaiki strategi fungsionalnya sesuai dengan arahan Islam.
Solusi pada Tataran Paradigmatik
Secara paradigmatik, pendidikan harus
dikembalikan pada asas aqidah Islam yang bakal menjadi dasar penentuan arah dan
tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum dan standar nilai ilmu pengetahuan
serta proses belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi guru/dosen serta
budaya sekolah/kampus yang akan dikembangkan. Sekalipun pengaruhnya tidak
sebesar unsur pendidikan yang lain, penyediaan sarana dan prasarana juga harus
mengacu pada asas di atas.
Melihat kondisi obyektif pendidikan saat
ini, langkah yang diperlukan adalah optimasi pada proses-proses pembentukan
kepribadian Islam (syakhshiyyah Islamiyyah) dan penguasaan tsaqafah
Islam serta meningkatkan pengajaran sains-teknologi dan keahlian sebagaimana
yang sudah ada dengan menata ontologi, epistemologi dan aksiologi keilmuan yang
berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sekaligus mengintegrasikan ketiganya).
Solusi pada Tataran Strategi Fungsional
Pendidikan yang integral harus melibatkan
tiga unsur pelaksana: yaitu keluarga, sekolah/kampus dan masyarakat. Buruknya
pendidikan anak di rumah memberi beban berat kepada sekolah/kampus dan menambah
keruwetan persoalan di tengah masyarakat. Sementara, situasi masyarakat yang
buruk jelas membuat nilai-nilai yang mungkin sudah berhasil ditanamkan di
tengah keluarga dan sekolah/kampus menjadi kurang optimum. Apalagi bila
pendidikan yang diterima di sekolah juga kurang bagus, maka lengkaplah
kehancuran dari tiga pilar pendidikan tersebut.
Dalam pandangan sistem pendidikan Islam,
semua unsur pelaksana pendidikan harus memberikan pengaruh positif kepada anak
didik sedemikian sehingga arah dan tujuan pendidikan didukung dan dicapai
secara bersama-sama, Kondisi tidak ideal seperti diuraikan di atas harus
diatasi.
Solusi strategis fungsional sebenarnya sama
dengan menggagas suatu sistem pendidikan alternatif yang bersendikan pada dua
cara yang lebih bersifat strategis dan fungsional, yakni: Pertama, membangun
lembaga pendidikan unggulan di mana semua komponen berbasis paradigma Islam,
yaitu: (1) kurikulum yang paradigmatik, (2) guru/dosen yang profesional, amanah
dan kafa’ah, (3) proses belajar mengajar secara Islami, dan (4)
lingkungan dan budaya sekolah/kampus yang kondusif bagi pencapaian tujuan
pendidikan secara optimal. Dengan melakukan optimasi proses belajar mengajar
serta melakukan upaya meminimasi pengaruh-pengaruh negatif yang ada, dan pada
saat yang sama meningkatkan pengaruh positif pada anak didik, diharapkan
pengaruh yang diberikan pada pribadi anak didik adalah positif sejalan dengan
arahan Islam.
Kedua, membuka lebar ruang interaksi
dengan keluarga dan masyarakat agar keduanya dapat berperan optimal dalam
menunjang proses pendidikan. Sinergi pengaruh positif dari faktor pendidikan
sekolah/kampus – keluarga – masyarakat inilah yang akan membuat pribadi anak
didik terbentuk secara utuh sesuai dengan kehendak Islam.
Berangkat dari paparan di atas, maka untuk mewujudkan lembaga pendidikan
unggulan yang dimaksud setidaknya terdapat empat komponen yang harus
dipersiapkan guna menunjang tindak solusi sebagaimana yang digagas, yakni
penyiapan kurikulum paradigmatik, sistem pengajaran, sarana prasarana dan
sumber daya guru/dosen.{Ђ}