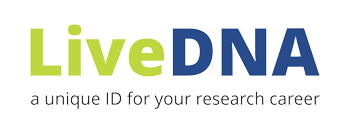Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu manusia melalui pengembangan fitrah (potensi diri). Manusia yang terdidik akan memiliki kekuatan spiritual agama, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam hidupnya. Oleh sebab itulah, pendidikan dianggap lebih identik dengan pekerjaan mengajar dan mendidik.
Seorang pendidik profesional sangat dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut. Tanggung jawab seorang pendidik tercermin dari sikap mengetahui dan memahami nilai, norma, dan sosial, serta berusaha berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Pendidik harus berwibawa, memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral dan sosial.
Pendidik harus cerdas, memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Ketika mengambil suatu keputusan pendidik harus mandiri (indefendent), terutama yang berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi. Pendidik juga harus visioner, bertindak sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan, bukan menanti perintah dari atasan semata. Pendidik juga harus disiplin, dalam arti mereka harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten.
Menurut konsep
al-Qur’an, pendidik merupakan sosok berkompetensi dalam membentuk manusia
sebagai hamba Allah yang mampu mengaktualisasi diri sesuai dengan syariat Islam
untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhiratnya. Pendidik memiliki peran yang
sangat besar dalam menyebarkan kebaikan melalui kegiatan pendidikan,
pembelajaran dan pelatihan. Pengembangan profesi pendidik seharusnya
tidak hanya terpaku pada hal-hal administrasi yang diatur juknis. Pendidik yang
sukses dengan meniru karakter yang disebutkan dalam al Quran (‘ulama, ar-rasikhuna
fi al-ilm, ahl dzikr, murabbi, muzakky, ulul albab, mawa’idz, dan mudarris, mu’allim dan mursyid).
Pendidik
sebagai ulama dapat dipahami dalam Q.S Al Fathir
(35:28). ‘Ulama adalah orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya ia
”takut” kepada Allah, memiliki akhlak mulia, menjadi teladan bagi masyarakat.
Seorang ‘ulama istiqamah terhadap ilmunya, serta berusaha
mengembangkan ilmunya secara terus-menerus, melakukan peran sebagai pelindung
dan pembimbing masyarakat.
Ilmu yang
dimiliki ulama bisa berupa ilmu agama (tafaqqahu fi al-din) atau ilmu
alam (sains). Semua ilmu pada hakekatnya berasal dari Allah
dan tugas utama seorang ulama adalah mengajarkan ilmu yang
menjadikan setiap orang yang belajar takut dan dekat kepada Allah. Pendidik
sebagai ulama menguasai ilmu secara mendalam, memiliki sifat ikhlas dan
pengabdian, sehingga dalam mengajarkan ilmunya didasari atas panggilan agama.
Pendidik
sebagai ar-rasikhuna fi al-ilm dapat dipahami berdasarkan
Q.S Ali Imran (3:7) Orang yang mendalam ilmunya, tidak hanya dapat
memahami ayat-ayat yang jelas dan terang maksudnya (muhkamat), juga memahami
ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian (interpretable). Ar-rasikhuna
fi al-ilm merupakan hamba yang memperoleh hidayah dari Allah,
iman mereka kokoh, taat menjalankan ibadah, memiliki kepedulian sosial, serta
berakhlakul karimah. Pendidik sewajarnya harus memiliki karakter
sebagai ar-rasikhuna fi al-’ilm, karena hampir sama
dengan karakter ulama. Bedanya, ulama tidak saja di bidang ilmu pengetahuan,
tetapi juga dalam kehidupan sosial. Sementara ar-rasikhuna fi al-’alm lebih
terkonsentrasi pada ilmu pengetahuan.
Pendidik
sebagai ahl dzikr terdapat dalam surat An-Nahl
(16:43). Ahl dzikr adalah orang yang memiliki pengetahuan,
menguasai masalah, atau ahli di bidangnya. Sebagai ahl dzikr,
setiap pendidik hendaklah menjadi orang yang selalu memberi peringatan kepada
orang lain agar meninggalkan perbuatan yang melanggar larangan Allah dan
Rasul-Nya. Pendidik sebagai ahl dzikr harus mendalami
ajaran-ajaran yang berasal dari Allah yang terkait dengan bidang keilmuannya.
Pendidik
sebagai Al murabbi terdapat dalam Q.S.
al-Fatihah (1:2). Kata Al murabbi seakar dengan
kata rabb atau tarbiyah, artinya pemelihara,
pendidik, atau menumbuh kembangkan. Allah adalah murabbi bagi
makhluk-Nya, dimana pendidikan Allah terhadap manusia terbagi dua, yaitu
pendidikan kejadian fisiknya serta pendidikan keagamaan dan akhlak. Al-Muraghi
menyebutkan bahwa al-Murabbi adalah orang yang memelihara,
mengajar dan membimbing tingkah laku. Pendidik sebagai al-Murabbi adalah
seseorang yang berusaha menumbuhkan, membina, membimbing, mengarahkan segenap
potensi peserta didik secara bertahap dan berkelanjutan. Al-Murabbi memiliki
tugas yang berat dalam membina aspek jasmani dan rohani manusia. Al
murabbi harus memiliki kesanggupan dan kecakapan jasmani dan rohani,
sehingga tugasnya yang berat tersebut dapat diaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Pendidik
sebagai Muzakki, terdapat dalam surat al Baqarah
(2:151). Muzakki berarti sebagai orang yang menyucikan. Dalam
konteks pendidikan, al-muzakki, adalah orang yang mampu membantu
manusia agar terhindar dari perbuatan yang keji dan munkar serta menjadi
manusia yang berakhlak mulia. Seorang muzakki memiliki
kemauan yang teguh untuk terus menerus mengajarkan manusia agar berupaya untuk
menyucikan diri, melakukan instropeksi secara terus menerus menjadi hamba Allah
yang baik.
Pendidik
sebagai ulul albab terdapat dalam surat Ali Imran
(3: 90-191). Ulul albab adalah orang yang
berzikir dan berpikir. Ulul albab merupakan orang yang
memiliki pemikiran (mind) luas dan dalam, perasaan (heart) halus
dan peka, daya pikir (intellect) tajam dan kuat, pandangan (insight)
luas dan dalam, pengertian (understanding) akurat, tepat, dan luas,
serta memiliki kebijaksanaan (wisdom). Ulul albab mampu
mendekati kebenaran dengan pertimbangan adil dan terbuka. Ulul
Albab adalah orang yang berakal atau orang yang dapat berfikir dengan
menggunakan akalnya, sehingga mampu ber pikir banyak dan beragam, tentang
ayat-ayat qauliyah (Al-Qur’an) dan ayat-ayat kauniyah (alam
semesta). Kemampuan berpikir ini bahkan mampu menganalisa secara mendalam
terhadap berbagai masalah yang mungkin terjadi, kemudian dapat menarik hikmah
atau pelajaran yang mendalam dari berbagai peristiwa
tersebut. Karakter ulul albab mengajarkan para
pendidik agar senantiasa menggunakan akalnya untuk memikirkan dan menganalisa
berbagai ajaran yang berasal dari Tuhan, peristiwa yang terjadi di sekitarnya
untuk diambil makna dan diajarkan kepada orang lain.
Pendidik
sebagai mawa’izh atau orang yang
memberi nasehat disebutkan dalam Q.S. Asy-Syu’ara (26:136). Mawa’izh adalah
orang yang senantiasa mengingatkan, menasehatkan dan menjaga orang yang
dididiknya dari pengaruh yang berbahaya. Nasehat itu berdasarkan kepada ajaran
al-Qur’an dan Hadis untuk melunakkan hati manusia, sehingga mereka menjadi
orang yang saleh, berprestasi dan terpelihara dari dosa-dosa.
Pendidik
sebagai al mudarris dapat dipahami dari akar kata
yang terdapat dalm Q.S al-An’am (6:105). Al mudarris merupakan
orang yang senantiasa melakukan kegiatan ilmiah seperti membaca, memahami,
mempelajari dan mendalami berbagai ajaran yang terdapat di dalam al-Qur’an dan
al-Sunnah. Setelah itu berupaya mengajarkan dan membimbing orang lain agar
memiliki tradisi ilmiah yang kuat.
Pendidik
sebagai mu’allim, berarti orang yang berilmu, istilah
ini tersirat dalam surat al-Baqarah (2:151). Makna ilmu dalam perspektif
Al-Qur’an lebih luas dan mendalam dari istilah knowledge, sains,
atau logos. Kata ilmu memiliki kaitan dengan alam, amal, dan al-‘alim.
Ilmu berkembang dengan mengkaji alam. Ilmu itu harus diamalkan, dan ilmu
tersebut mesti mendekatkan diri kepada al-’Alim, yaitu Allah Yang
Maha Memiliki Ilmu. Mu’allimmesti mengajarkan ilmu yang terkait
dengan kognisi, psikomotor, dan afeksi. Mu’allim bertanggung
jawab untuk mengajarkan ilmu untuk diamalkan dan mendekatkan diri kepada Allah.
Pendidik
sebagai mursyd bermakna orang yang cerdas. Mursy berasal
dari kata rasyada, artinya cerdas. Istilah ini terkandung dalam
surat an-Nisa’ (4:6). Cerdas dimaksud tidak saja pada intelektualitasnya,
tetapi berhubungan erat dengan spiritualnya. Dalam sebuah kisah disebutkan,
pada suatu ketika, Imam Syafi’i berkata: ”saya mengadu kepada Waqi’ tentang
buruknya hafalanku, maka dia mengajarkanku (fa arsyadani) agar
meninggalkan maksiat. Dan ia mengabarkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya (nur),
dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat”. Nasehat Waqi’ tersebut
mengajarkan agar Syafi’i cerdas (irsyad) dengan meninggalkan kemaksiatan.
Karakter pendidik sebagai mursyid, berarti pendidik
harus menjadi orang yang cerdas baik dalam penguasaan materi,
penerapan teknik dan metode, serta menjadi model, teladan atau tokoh yang jauh
dari perbuatan-perbuatan maksiat.
Kesepuluh
istilah di atas menunjukkan bahwa seorang pendidik tidak sekedar penyampai
materi, tetapi yang terpenting adalah melakukan internalisasi
nilai yang berbasis Al-Qur’an. Pendidik dituntut untuk membaca,
mengkaji, mengamalkan dan mengajarkan ayat-ayat Al-Qur’an sesuai dengan bidang
keilmuan yang dimilikinya. Dengan begitu tidak boleh berhenti belajar,
meskipun telah mengajar. Pendidik harus tetap belajar membina dan mendidik
dirinya sendiri sehingga berhasil mendidik orang lain.
Bahan Bacaan
Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the
Criminal Justice System. In International Statistics on Crime and Justice
(pp. 87–109). Helsinki: HEUNI Publication.
Abdullah, A., &
Tabrani ZA. (2018). Orientation of Education in Shaping the Intellectual
Intelligence of Children. Advanced Science Letters, 24(11),
8200–8204. https://doi.org/10.1166/asl.2018.12523
AR, M., Usman, N.,
Tabrani ZA, & Syahril. (2018). Inclusive Education Management in State
Primary Schools in Banda Aceh. Advanced Science Letters, 24(11),
8313–8317. https://doi.org/10.1166/asl.2018.12549
Idris, S., &
Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan
Islam. JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling, 3(1), 96–113.
https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420
Idris, S., Tabrani ZA,
& Sulaiman, F. (2018). Critical Education Paradigm in the Perspective of
Islamic Education. Advanced Science Letters, 24(11), 8226–8230.
https://doi.org/10.1166/asl.2018.12529
Murziqin, R., &
Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the
Electoral in Aceh. Journal of Islamic Law and Culture, 10(2),
123–144.
Murziqin, R., Tabrani
ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and
Justice. Journal of Islamic Law and Culture, 10(2), 123–144.
Musradinur, &
Tabrani ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam Pluralis Sebagai Solusi
Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana Pendidikan Pluralisme Indonesia). 1st
Annual International Seminar on Education 2015, 77–86. Banda Aceh: FTK
Ar-Raniry Press.
Patimah, S., &
Tabrani ZA. (2018). Counting Methodology on Educational Return Investment. Advanced
Science Letters, 24(10), 7087–7089. https://doi.org/10.1166/asl.2018.12414
Tabrani ZA. (2009). Ilmu
Pendidikan Islam (antara Tradisional dan Modern). Kuala Lumpur:
Al-Jenderami Press.
Tabrani
ZA. (2013a). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan
Islam (Tantangan Terhadap Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah). Jurnal
Ilmiah Serambi Tarbawi, 1(2), 65–84.
Tabrani ZA. (2013b). Pengantar
Metodologi Studi Islam. Banda Aceh: SCAD Independent.
Tabrani ZA. (2013c).
Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Sintesa, 13(1),
91–106.
Tabrani ZA. (2014a). Buku
Ajar Filsafat Umum. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
Tabrani ZA. (2014b). Dasar-Dasar
Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Darussalam Publishing.
Tabrani ZA. (2014c).
Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu Kajian Gradual Menuju
Paradigma Global). Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2(2), 211–234.
Tabrani ZA. (2014d).
Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Islam Perspektif Pedagogik Kritis. Jurnal
Ilmiah Islam Futura, 13(2), 250–270. https://doi.org/10.22373/jiif.v13i2.75
Tabrani ZA. (2014e).
Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur`an dengan Pendekatan Tafsir Maudhu`i.
Jurnal Ilmiah Serambi Tarbawi, 2(1), 19–34.
Tabrani ZA. (2015a). Arah
Baru Metodologi Studi Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Tabrani
ZA. (2015b). Keterkaitan Antara Ilmu Pengetahuan dan Filsafat (Studi Analisis
atas QS. Al-An`am Ayat 125). Jurnal Sintesa, 14(2), 1–14.
Tabrani ZA. (2015c). Persuit
Epistemology of Islamic Studies. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Tabrani ZA. (2016a).
Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis Geo-Kultur Islam dan Politik Pada
Kerajaan Turki Usmani). JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling, 2(2),
130–146. https://doi.org/10.22373/je.v2i2.812
Tabrani ZA. (2016b).
Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang
Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). Al-Ijtima`i-International
Journal of Government and Social Science, 2(1), 41–60.
Tabrani ZA. (2017b).
Restrukturrisasi untuk Pendidikan Bermutu. Research in Education, 12(1),
131–136.
Tabrani ZA. (2017c). دور التربية الإسلامية في الإنماء الخلقي للشعب (دراسة على
الإسلام ودوره في الإنماء القومي بإندونيسيا). Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies, 4(1),
101–116. https://doi.org/10.20859/jar.v4i1.128
Tabrani ZA. (2019).
Social Change and Human Nature. In The New System’s Need for Primitive
Capital Accumulation (pp. 271–277). United Kingdom: Taylor & Francis.
Tabrani ZA, &
Hayati. (2013). Buku Daras Ulumul Quran (1). Yogyakarta: Darussalam
Publishing.
Tabrani ZA, &
Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence
in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern
Learning Theories). JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling, 1(2),
99–112. Retrieved from
http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/cobaBK/article/view/600
Tabrani ZA, &
Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa
Ni’mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. Ijtima`i: International Journal of
Government and Social Science, 3(1), 15–30.
Tabrani ZA. (2019b). Konfigurasi
Pendidikan Karakter dalam Konteks Totalitas Proses Psikologis dan
Sosial-Kultural. Ethics and Education, 12(1), 13–20.
Usman, N., AR, M.,
Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2018). The Principal’s Managerial Competence
in Improving School Performance in Pidie Jaya Regency. Advanced Science
Letters, 24(11), 8297–8300. https://doi.org/10.1166/asl.2018.12545
Usman, N., AR, M.,
Syahril, Irani, U., & Tabrani ZA. (2019). The implementation of learning
management at the institution of modern dayah in aceh besar district. Journal
of Physics: Conference Series, 1175(1), 012157.
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012157
Walidin, W., Idris,
S., & Tabrani ZA. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif &
Grounded Theory. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
Warisno, A., &
Tabrani ZA. (2018). The Local Wisdom and Purpose of Tahlilan Tradition. Advanced
Science Letters, 24(10), 7082–7086.
https://doi.org/10.1166/asl.2018.12413