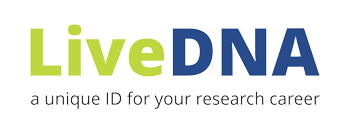Oleh:
Akhiriyati Sundari (Mahasiswa Islam dan Kajian Gender UIN Sunan Kalijaga)
Pendahuluan
Tubuh perempuan selalu memasuki hiruk-pikuk pembahasan di segala ranah.
Karenanya tidak ada diskursus lain yang memiliki daya tanding lebih yang mampu
menyamai atau menyaingi diskursus ramai atasnya kecuali perbincangan tentang
tubuh perempuan. Tubuh perempuan dari masa ke masa selalu mengalami kontestasi
untuk diperebutkan oleh pihak-pihak yang berasal dari luar dirinya. Konstruksi
sosial yang ditopang oleh ragam struktur sosial, berkembang setingkat
dinamika yang mengiringi laju jaman. Ada titik yang dibidik sekaligus disasar
dari perebutan wacana dan tubuh perempuan, yakni ketundukan dan kepasrahan.
Dalam hal ini pihak laki-laki adalah tertuduh utama dengan bias sekaligus eros patriarkalnya, yang
selalu merasa memiliki ‘hak istimewa’ untuk membuat berbagai penilaian atas
tubuh perempuan. Laki-laki merasa seakan memiliki privilese untuk mengintervensi
dengan meletakkan standar nilai tertentu kepada tubuh perempuan. Semuanya
bekerja dalam bingkai patriarki yang mendudukkan posisi perempuan dan tubuhnya
dalam posisi subordinat. Dimensi kekuasaan digunakan sebagai mesin kerja untuk
mencapai tujuan.
Foucault dalam masterpiece-nya
tentang seksualitas mengatakan bahwa gagasan seksualitas dan kekuasaan sangat
membantu analisis sosial dalam mengurai berbagai ketimpangan akibat relasi
kekuasaan yang tidak seimbang terutama dalam kehidupan modern. Dalam perspektif
ini, kekuasaan sebagai rezim wacana dianggap mampu menggapai, menembus, dan
mengontrol individu sampai kepada kenikmatan-kenikmatan yang paling intim.
Kekuasaan sebagai rezim wacana ini dianggap sebagai praksis yang mampu mengubah
konstelasi sosial. Darinya lalu muncul pengetahuan sebagai daya topang
kekuasaan. Hubungan kekuasaan dan pengetahuan ini menurut Foucault adalah
ketika wacana yang ada menahbiskan dirinya sebagai yang memiliki otoritas,
otonomi atas klaim kebenaran dan kontekstual, seperti yang ada pada psikiatri,
kedokteran, pendidikan, dan agama.
Di dalam Islam, tubuh perempuan diidentifikasi sebagai yang memiliki rahim.
Konteks mikronya bahwa hal ini mengindikasikan perempuan sebagai jenis kelamin
yang ‘membawa kehidupan’, lengkap dengan sifat rahim [baca: kasih sayang] yang meng-endors pada wujud rahim di
dalam tubuhnya. Sedang konteks makronya adalah perempuan memiliki keistimewaan
yang khas dan tak bisa dipertukarkan. Karenanya Islam sangat menghormati
perempuan sebagai manusia utuh yang sama dengan laki-laki. Titik tekan Islam
paling utama dalam membingkai perbedaan laki-laki dan perempuan hanyalah pada
tingkatan amal saleh. Yakni sejauh mana kedua jenis kelamin berlomba-lomba
dalam berbuat kebajikan dan bermanfaat bagi orang lain. Suara Islam yang genius
ini kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat dimana konstruksi sosial
patriarkalnya amat parah. Budaya yang lestari pada akhirnya menjadi tungkai
bajak dan mengeliminir semangat universal Islam yang terkandung dalam kitab
suci.
Membincang Seksualitas dalam Wacana Islam: Pernikahan
Wacana Islam dimaksud di sini adalah segala hal yang terbingkai dalam
segala dialektika dan perdebatan tentang Islam. Bangunan terpenting yang
menjadi acuan wacana ini adalah bersumber dari kitab suci [Syafiq Hasyim,
2002]. Bagaimana Al-Qu’ran sebagai kitab suci berbicara tentang seksualitas?
Tentu saja hal ini terkait dengan pola relasi laki-laki dan perempuan di dalam
Islam. Ranahnya adalah seputar perkawinan, perceraian, relasi pergaulan
suami-istri di dalam rumah tangga, masa tunggu sesudah bercerai [iddah], hingga persoalan yang
menyangkut homoseksualitas.
Kitab suci membingkai urusan seksualitas di dalam Islam hanya boleh
dilakukan melalui lembaga perkawinan. Hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan
dianggap ilegal disebut sebagai zina. “Dan janganlah kamu mendekati zina karena
itu sekeji-kejinya perbuatan” [QS Al-Isra (17): 32], ayat yang keras melarang
perbuatan zina dengan penekanan ‘mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan’
ini sesungguhnya hendak merespon masa lalu, dimana jaman pra-Islam, kegiatan
seksual dapat dilakukan dengan bebas tanpa ikatan pernikahan sekalipun.
Terpapar di dalam kitab suci pula bentuk respon terhadap masa lalu adalah
dengan membatasi kepemilikian istri menjadi maksimal empat. Struktur sosial
bangsa Arab pada masa pra-Islam yang disebut sebagai jahiliyah telah menempatkan
perempuan sebagai istri yang bermakna ‘properti’. Hanya barang yang diambil
kegunaannya semata sehingga dalam satu keluarga sebagai struktur sosial
terkecil, adalah lumrah terdapat sembilan bahkan ratusan istri [poligami, pada
kepala-kepala suku bangsa pagan kala itu]. Lantaran barang yang hanya diambil
kegunaannya maka si pemilik properti [suami] bebas untuk berbuat sesuka
hatinya, misal dengan mencampakkan begitu saja ketika merasa si istri sudah
tidak berguna. Dari sini tampak secara jelas bahwa poligami bukanlah ajaran
Islam, melainkan telah ada sebagai produk sosial umat terdahulu.
Semangat yang disuntikkan Islam adalah memartabatkan manusia dalam
resapan-resapan cinta melalui hubungan perkawinan sebagai hal alami yang
naluriah. Lebih lanjut Al-Qur’an kemudian memberikan topangan spiritual
bagaimana laki-laki dan perempuan yang terikat di dalam lembaga perkawinan itu
seharusnya bergaul. Ada relasi yang setara dan seimbang, sebagai prasyarat
mutlak yang harus diketahui untuk mencapai tujuan harmoni, bermartabat, dan
bermoral. Metafora indah “mereka [para istri itu] adalah pakaian bagimu dan
kamu adalah pakaian bagi mereka” [QS Al-Baqarah [1]: 187], menunjukkan bahwa
masing-masing relasi adalah resiprokal seimbang. Pakaian bersifat menutupi,
memperindah, dan melindungi. Seyogyanya demikian pula dalam relasi suami-istri.
Kasih sayang dan cinta kasih adalah perlambang adibusana, karenanya suami-istri secara moral
dilarang saling menyakiti, secara moral harus menghargai dan menghormati satu
sama lain dengan menghindari hegemoni-dominasi, termasuk dalam urusan seksual.
Fatima Mernissi menyebut bahwa Al-Qur’an sesungguhnya tidak pernah
menjustifikasi poligami. Justru Al-Ghazali lah yang melakukannya, karenanya
Mernissi menganggap bahwa bahwa ada kekeliruan dari para pemikir Islam, yang
tidak melihat poligami sesungguhnya sangat merugikan perempuan dengan tidak
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan perempuan yang harus dipertimbangkan dalam
praktik pergaulan yang ma’ruf tersebut,
terutama pada kebutuhan seksual istri. Poligami dipandang sebagai lebih jauh
dari sekadar memberikan hak seksual laki-laki, yakni menyediakan ruang bagi
laki-laki untuk memperturutkan hawa nafsu seksualnya tanpa kenal batas. Padahal
dalam adagium populer telah gamblang dikatakan bahwa ‘nafsu [seksual] itu
seperti anak kecil [bayi] yang menyusu, ia akan terus meminta’.
Selain sumber kitab suci, dalam wacana Islam terkait seksualitas, sunnah
Nabi Muhammad SAW adalah rujukan penting kedua. Sunnah Nabi mencakup ucapan,
tindakan/perilaku dan hal-hal atau peristiwa apa saja yang dilangsungi selama
hidupnya. Nabi Muhammad sebagai orang suci dan dipilih oleh Tuhan dengan
status ma’shum,
bebas dari salah—lantaran seluruh makrokosmos dan mikrokosmos hidupnya adalah
wahyu Tuhan, menjadi duplikasi yang tampak mata sebagai ejawantah ajaran kitab
suci. Sejarah hidup Nabi mengisahkan perkawinannya dengan Siti Khadijah
didahului oleh lamaran yang dilakukan Khadijah. Bukan oleh Nabi sendiri,
melainkan Khadijah yang meminta. Perkawinannya dilandasi cinta dan saling
penghormatan. Garis bawah dari sejarah telah mencatat bahwa Khadijahlah yang
aktif dan Nabi pasif, menerima. Terlepas dari status kelas yang melekat pada
diri Khadijah sehingga yang bersangkutan dimungkinkan memiliki ‘daya aktif’
melamar, di situ sekali lagi memperlihatkan ada keterlibatan perempuan dalam
tindakan ‘memulai lebih dulu’ terhadap pasangannya. Tidak ada penolakan sama
sekali dari Nabi, artinya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Landasan ini
pulalah yang dapat dipakai sebagai teropong bahwa dalam kehidupan seksual
suami-istri, kedua belah pihak setara, tidak selalu suami yang aktif, tetapi
istri pun. Tidak ada ordinat dan subordinat dalam relasi perkawinan Nabi dan
Khadijah. Bahkan tidak mempermasalahkan status diri Khadijah sebelum menikah
dengan Nabi.
Kekuasaan Pengetahuan: Memasung Seksualitas Perempuan
Perebutan wacana di dalam fungsi otorisasi akan klaim kebenaran terhadap
tubuh perempuan sesungguhnya telah berlangsung sekian lama di dalam Islam.
Idealisasi yang termaktub dalam kitab suci berikut sejarah Islam awal yang
dibangun oleh Nabi Muhammad direduksi secara kasar sejak Nabi wafat. Dimulai
dari jaman kekhalifahan empat hingga mengecambah ke dinasti-dinasti politik
sesudahnya, posisi perempuan ‘dikembalikan’ ke dalam rumah. Ke ranah domestik.
Ketika jaman Nabi perempuan turut pula terlibat aktif di ranah publik tak
terkecuali dalam urusan ibadah ritual di masjid, maka sesudah Nabi wafat
perempuan bahkan tidak boleh pergi ke masjid. Maka dimulailah aneka ketimpangan
dan ketidakadilan terhadap perempuan itu termasuk di ranah seksual. Perempuan
mengalami berbagai tindakan tidak adil juga kekerasan terkait seksual.
Mengutip Abdul Munir Mulkhan [2002], sedikitnya ada tiga persoalan
menyangkut ketidakadilan seksual pada perempuan; pertama, tradisi Islam dalam
fikih [formula aturan hukum yang berkembang pasca Nabi] yang menempatkan
perempuan sebagai ‘pelayan kebutuhan seksual laki-laki’ dan ‘pembangkit birahi
seksual’. Kedua,
kecenderungan konsumerisme tubuh perempuan dalam peradaban industri
modern. Ketiga,
tradisi lokal [khususnya Jawa] yang masih melekatkan stereotype kepada perempuan
sebagai ‘penumpang’ kemuliaan [kelas sosial] laki-laki. Ketiga, persoalan itu
berkelindan dan melahirkan gagasan subordinasi pada perempuan.
Gagasan yang menumbuh pada relasi kuasa yang timpang ini tak ayal
menumbuhkan bibit-bibit kekerasan seksual terhadap perempuan. Perempuan hanya
dilihat sebagai seonggok daging bernama tubuh seksual. Subjek yang melihat
adalah laki-laki. Melihat di sini dimaknai sebagai penguasa tatapan. Foucault
menganasir hal ini sebagai tindakan kekuasaan-pengetahuan yang menerapkan
strategi kekuasaannya untuk mengatur [seksualitas] perempuan. Ada histerisasi
tubuh perempuan yang menunjukkan bahwa tubuh [perempuan] dikaitkan dengan tubuh
sosial untuk menjamin kesuburan dan semua bentuk kewajiban yang datang dari
keluarga termasuk kehidupan anak. Jadi tubuh perempuan tidak bisa dilepaskan
dari tanggung jawab biologi dan moral. Khasanah fikih klasik hingga hari ini
masih memberikan kacamata patriarki yang sarat bias gender dalam mengatur
seksualitas perempuan.
Khitan perempuan, sebagai contoh, dikatakan bahwa ia adalah perintah agama.
Padahal sesungguhnya sunat perempuan adalah tradisi yang berasal dari 4000
tahun sebelum Nabi Isa lahir. Ada pada masa Fir’aun, karenanya dulu dikenal
dengan istilah pharaonic
circumcisium [Jurnalis Uddin, 2013]. Hingga kini hanya di
Yaman, Irak, Iran, Pakistan, India, Malaysia, dan Indonesia. Alasan dibalik
pelaksanaan khitan perempuan ini adalah untuk mengerem nafsu seksual perempuan,
yang dianggap lebih besar kadarnya daripada laki-laki sehingga membahayakan.
Anggapan ini semata adalah mitos. Produk sosial dari jaman Fir’aun. Akan
tetapi, institusi agama melestarikannya sebagai bagian dari ajaran agama. MUI
tahun 2008 melakukan penolakan terhadap edaran Kementerian Kesehatan tahun 2007
yang melarang pelaksanaan khitan perempuan dari sudut pandang medis [Jurnal
Perempuan 77].
Ketegangan pihak pemegang otoritas agama terhadap entitas di luarnya,
adalah bentuk dari perebutan wacana tubuh perempuan. Sebagai medan politik,
tubuh perempuan ditundukkan. Tubuh perempuan dipindai dengan tatapan laki-laki
dus patriarki dalam sederet stigma negatif. Ada yang buruk dalam tubuh
perempuan sekaligus ada yang menguntungkan dari tubuh perempuan. Tatapan
patriarki ini lalu dilanggengkan dalam struktur sosial, mengokohkan diri
sebagai pemegang kekuasaan.
Strategi kedua menurut Foucault dari permainan kekuasaan-pengetahuan adalah
pedagogisasi seks anak dengan tujuan anak jangan sampai jatuh dalam aktivitas
seksual, karena mengandung bahaya fisik dan moral serta dampak kolektif maupun
individual. Pedagogisasi ini juga untuk melawan onanisme [Haryatmoko, 2013].
Dalam setiap generasi sejak kecil, diajarkan tentang bahaya seksualitas
yang dilakukan tidak di dalam pernikahan. Institusi agama membingkainya dalam
fikih yang masih normatif, yang mengajarkan hanya ketakutan tanpa didukung oleh
pengetahuan positif yang memadai. Anak tidak diberikan pendidikan seksualitas
sejak dini lantaran anggapan tabu. Sehingga anak telah sejak dini pula
dijauhkan dari pengetahuan yang memadai tentang tubuhnya. Otoritas agama hanya
berkutat di seputar fikih yang lebih banyak mengatur soal thoharoh [tata aturan
kebersihan] dalam kaitannya dengan sembahyang wajib [termasuk di dalamnya
batasan tentang menutup aurat di dalam sholat]. Disusupkan pendidikan moral di
dalamnya semata bahwa lagi-lagi tubuh perempuan adalah ‘sumber dosa’, karena
itu jangan dekat-dekat.
Walhasil, tidak mengherankan ketika pedagogisasi ini di lain pihak justru
mengungkung hak anak untuk mengetahui kesehatan reproduksi secara benar. Saat
marak kasus pernikahan dini, pernikahan anak-anak usia remaja ke bawah,
persoalan-persoalan terkait kesehatan reproduksi dan seksual ini menjadi kian
rumit dan blunder. Tidak ada kesiapan mental dan fisik. Anak-anak didorong
begitu saja masuk ke kegelapan dunia seksualitas sehingga rentan dengan bahaya
yang sulit dihindari seperti AKI, anemia, pendarahan, ekslampsia, juga tidak
menutup kemungkinan penyakit menular seksual.
Kasus pernikahan anak ini juga tidak bisa begitu saja dilepaskan dari
konstruksi masyarakat yang digarisbawahi oleh tafsir-tafsir agama. Kerapkali
misalnya, menganggap bahwa pernikahan anak akan menyelamatkan si anak dari
pergaulan buruk yang menggiring pada hubungan seksual diluar pernikahan
sebagaimana dilarang oleh agama, apalagi anak perempuan korban perkosaan
[kekerasan seksual]. Ada pula yang menyandarkan diri pada sejarah Nabi bahwa
pernikahannya dengan Siti Aisyah adalah termasuk pernikahan dini, karenanya
dipandang sebagai sebuah syariat yang harus dipatuhi. Belum ditambah lagi
argumen yang dipaksakan dan direkayasa secara panjang oleh konstruksi sosial
stigmatis di masyarakat, bahwa pernikahan anak lebih baik daripada perempuan
yang sudah ‘cukup umur’ namun belum menikah. Status single perempuan
distigmatisasi oleh patriarki sebagai ‘kerawanan sosial’. Pernikahan anak juga tidak
jarang bermotifkan ekonomi yang lagi-lagi ditopang oleh agama bahwa menghindari
kemiskinan itu wajib agar tak terjerembab ke kekufuran. Tidak bisa tidak
menurut tafsir ini, solusinya adalah menikahkan anak.
Instrumen ini secara terus-menerus melanggengkan relasi kuasa yang timpang
dalam mengatur seksualitas perempuan. Selanjutnya menurut Foucault, adanya
sosialisasi perilaku prokreatif dimaksudkan untuk kesuburan pasangan;
sosialisasi politik dilaksanakan melalui tanggung jawab pasangan terhadap tubuh
sosial; dan sosialisasi medik termasuk praktik kontrol kelahiran atau KB. Pada
masa Orde Baru, tangan otoritas keagamaan bergandeng tangan dengan kekuasaan
untuk melakukan pengontrolan tubuh perempuan melalui program KB. Nilai
keagamaan berlabuh dalam program yang sarat kepentingan politik negara dalam
biopolitik modern. Tubuh perempuan menjadi sasaran utama ragam alat kontrasepsi
tanpa mempertimbangkan kebutuhan kesehatan tubuh perempuan itu sendiri.
Perempuan ditekan untuk tidak memiliki kedaulatan atas tubuhnya sendiri.
Strategi kuasa pengetahuan sebagaimana diungkap Foucault di atas sejatinya
dijadikan instrumen oleh agama melalui pengendalian atas tubuh perempuan.
Subjek yang saling mengait ini memiliki tujuan yang satu yakni kepatuhan dan
ketundukan. Darinya maka sebuah rezim akan langgeng dalam status quo. Seluruh peristiwa
ini dibingkai dari frame patriarki yang mengusung rezim seksualitas dalam
agama.
Kuasa pengetahuan selanjutnya hadir dalam problem modernitas yang
melahirkan anak kandung bernama kapitalisme. Di wilayah ini, tubuh perempuan
diperebutkan kembali untuk dijadikan objek konsumerisme. Tidak terkecuali tubuh
perempuan yang ditarik melalui wilayah keagamaan yang dipromosikan melalui
media. Terdapat rezim kapitalisme di sini yang berhasrat hanya untuk penumpukan
kapital.
Standar tubuh perempuan dilabeli oleh patriarki melalui narasi-narasi
perempuan ideal, cantik, langsing, berkulit putih, lembut, berambut panjang,
bisa melahirkan anak, dan sederet panjang ukuran-ukuran subjektif lainnya, kemudian
direproduksi oleh media secara massif dan vandalistik. Tidak terbatas pada
media-media yang hanya dipajang dan dilihat secara dekat melalui media
elektronik dan media cetak, persepsi patriarki atas tubuh perempuan dinarasikan
pula secara jauh melalui ‘sampah visual’ yang bertebaran di ruang-ruang publik
dengan tak terkendali. Baliho-baliho, spanduk, dan billboard berkibar gemebyar,
menyesaki ruang-ruang publik di jalanan, berjajar-jajar tak karu-karuan dengan
tiang-tiang serta kabel-kabel listrik yang bergelantungan sebagai penanda
buruknya sistem tata kota di negara yang gamang dengan modernitas ini.
Idealitas dalam wilayah tafsir agama yang membungkus perempuan dengan
penertiban moral, turut pula diblow-up media dengan narasi-narasi ‘iklan
syariah’. Iklan perempuan berjilbab sebagai contoh, tak ketinggalan memasuki
arena publik dalam promo massal produk-produk tertentu berlabel agama [contoh
jilbab zoya bersertifikat halal]. Tubuh perempuan lagi-lagi direbut otonominya
di sini sebagai pendulang pundi-pundi dalam bingkai kapitalisme. Bahwa
perempuan muslim yang kaffah selain membungkus tubuhnya dengan hijab agar tak
mengundang birahi laki-laki, juga harus memastikan bahwa produk yang dipakainya
adalah halal [berlisensi islami]. Begitu ribetnya tubuh perempuan harus
didorong melesak ke dalam kapitalisme berjubah agama. Rezim seksualitas
dihasilkan dari koalisi halus antara kapitalisme dan agama.
Penutup
Tubuh perempuan disorot dan diregulasikan dalam kancah paling esensial dari
laku hidup manusia [agama], melalui penertiban perilaku, pakaian, dan
segmen-segmen hidup yang lain. Tafsir-tafsir agama diwacanakan secara massif
tanpa celah kritis sedikit pun, untuk memberikan satu narasi tunggal
tentang stereotype perempuan
melalui presentasi sebagai konstruksi cultural, yakni media. Bahwa media adalah
struktur yang paling berperan dalam mereproduksi cara masyarakat mendudukkan
dan memandang perempuan. Cara pandang ini diadopsi untuk memperlihatkan
kekuatan media dan otoritas mainstream keagamaan dalam membentuk opini yang
mendukung pandangan dominan tentang perempuan.
Tubuh perempuan dikontrol agar menjalani ketundukan dan kepatuhan dengan
frame patriarki, ditopang secara kokoh oleh sebuah rezim seksualitas. Pada
akhirnya, dalam gerusan modernitas yang terus-menerus dipiyuh oleh kapitalisme
ini, tubuh perempuan mulai kehilangan otonomi. Pada setiap laju sejarah, hal
ini akan terus dimainkan sebagai ajang politik, padahal sejatinya justu
menunjukkan sebuah tontonan lemah dari patriarki yang tidak pernah bisa menundukkan
ego pallus-nya.
Referensi
Abdul Moqsit Ghozali, Badriyah Fayumi,
dkk, Tubuh, Seksualitas, dan
Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Cirebon:
Rahima. 2002.
Christina Siwi Handayani, Gadis Arivia,
dkk, Subyek yang Dikekang;
Pengantar ke Pemikiran Julia Kristeva, Simone de Beauvoir Michel Foucault,
Jacques Lacan, Jakarta: Komunitas Salihara. 2013.
Idris, S & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme
dalam Konteks Pendidikan Islam. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 3(1),
96-113.
Irwan Abdullah, Nasaruddin Umar,
dkk, Islam dan Konstruksi
Seksualitas, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2001.
Jeremy R. Carette (ed.), Agama, Seksualitas, Kebudayaan; Esai,
Kuliah, dan Wawancara Terpilih Michel Foucault, Yogyakarta:
Jalasutra. 2011.
Jurnal Perempuan edisi 15, “Wacana Tubuh
Perempuan”. 2001.
Jurnal Perempuan edisi 71, “Perkosaan dan Kekuasaan”. 2011.
Jurnal Perempuan edisi 77, “Agama dan Seksualitas”. 2013.
remotivi.com, “Perempuan tanpa Otonomi; Wajah Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan”. 2014.
remotivi.com, “Perempuan tanpa Otonomi; Wajah Ideologi Dominan dalam Sinetron Ramadhan”. 2014.
Michel Foucault, Kuasa/Pengetahuan, Yudi Santosa
(penerj.), Yogyakarta:
Bentang Budaya. 2002.
Mochamad Sodik (ed.), Telaah Ulang Wacana Seksualitas,
Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga. 2004.
Musradinur
& Tabrani. ZA. (2015). Paradigma Pendidikan Islam
Pluralis Sebagai Solusi Integrasi Bangsa (Suatu Analisis Wacana Pendidikan
Pluralisme Indonesia). Proceedings 1st Annual International Seminar on
Education 2015.
Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 77-86
Tabrani. ZA & Hayati.
(2013). Buku Ajar Ulumul Qur`an (1). Yogyakarta:
Darussalam Publishing, kerjasama dengan Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
Tabrani. ZA & Masbur, M. (2016). Islamic Perspectives on
the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical
Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan
Konseling, 1(2),
99-112.
Tabrani.
ZA. (2008). Mahabbah dan Syariat. Selangor: Al-Jenderami Press
Tabrani.
ZA. (2009). Ilmu Pendidikan Islam (Antara Tradisional dan Modern). Selangor: Al-Jenderami
Press
Tabrani. ZA. (2011).
Dynamics of Political System of Education Indonesia. International Journal
of Democracy, 17(2), 99-113
Tabrani. ZA. (2011). Nalar
Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik
Pendidikan Indonesia). Millah Jurnal Studi Agama, 10(2), 395-410
Tabrani.
ZA. (2011). Pendidikan Sepanjang Abad (Membangun Sistem Pendidikan Islam di
Indonesia Yang Bermartabat). Makalah disampaikan pada Seminar Nasional 1
Abad KH. Wahid Hasyim. Yogyakarta: MSI UII, April 2011.
Tabrani. ZA. (2012). Future
Life of Islamic Education in Indonesia. International Journal of Democracy,
18(2), 271-284
Tabrani. ZA. (2012). Hak
Azazi Manusia dan Syariat Islam di Aceh. Makalah disampaikan pada International
Conference Islam and Human Right, MSI UII April 2012, 281-300
Tabrani.
ZA. (2013). Kebijakan Pemerintah dalam
Pengelolaan Satuan Pendidikan Keagamaan Islam (Tantangan Terhadap Implementasi
Manajemen Berbasis Sekolah), Jurnal Ilmiah Serambi Tarbawi, 1(2),
65-84
Tabrani.
ZA. (2013). Modernisasi Pendidikan Islam (Suatu Telaah Epistemologi
Pendidikan), Jurnal Ilmiah Serambi Tarbawi, 1(1), 65-84
Tabrani.
ZA. (2013). Pengantar Metodologi Studi
Islam. Banda Aceh: SCAD
Independent
Tabrani.
ZA. (2013). Urgensi Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal
Sintesa, 13(1), 91-106
Tabrani.
ZA. (2014). Buku Ajar Filsafat Umum. Yogyakarta: Darussalam Publishing, kerjasama
dengan Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
Tabrani.
ZA. (2014). Buku Ajar Penelitian Tindakan Kelas (PTK) (Bahan Ajar untuk
Mahasiswa Program Srata Satu (S-1) dan Program Profesi Keguruan (PPG)). Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press
Tabrani.
ZA. (2014). Dasar-Dasar Metodologi
Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Darussalam Publishing
Tabrani. ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner
(Suatu Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2(2),
127-144.
Tabrani.
ZA. (2014). Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan
Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura,
13(2), 250-270
Tabrani. ZA. (2014). Menelusuri Metode Pendidikan dalam Al-Qur`an dengan Pendekatan Tafsir
Maudhu`i. Jurnal Ilmiah Serambi Tarbawi, 2(1),
19-34
Tabrani.
ZA. (2015). Arah Baru Metodologi Studi
Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Tabrani.
ZA. (2015). Keterkaitan Antara Ilmu Pengetahuan dan Filsafat (Studi
Analisis atas QS. Al-An`am Ayat 125). Jurnal Sintesa, 14(2), 1-14
Tabrani.
ZA. (2015). Persuit Epistemologi of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru
Metodologi Studi Islam). Yogyakarta:
Penerbit Ombak
Tabrani.
ZA. (2016). Aliran Pragmatisme dan
Rasionalisasinya dalam Pengembangan Kurikulum 2013, dalam Saifullah Idris
(ed.), Pengembangan Kurikulum: Analisis Filosofis dan Implikasinya dalam
Kurikulum 2013, Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press 2016
Tabrani. ZA. (2016). Perubahan Ideologi Keislaman Turki (Analisis
Geo-Kultur Islam dan Politik Pada Kerajaan Turki Usmani). Jurnal
Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 2(2), 130-146.
Tabrani.
ZA. (2016). Transpormasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah Singkat
Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). Al-Ijtima`i- International
Journal of Government and Social Science, 2(1), 41-60
Walidin, W., Idris, S &
Tabrani. ZA. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory. Banda
Aceh: FTK Ar-Raniry Press