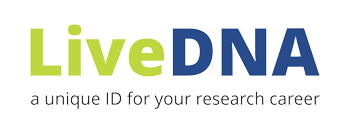ARISTOTELES sangat berpengaruh amat besar dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan,
seperti logika, fisika, metafisika, etika, ketatanegraandan lain-lainnya. Pengaruh
yang lebih besar adalah logika. Kalau pengaruh Aristoteles setelah zaman
Renaisans mulai berkurang,maka dalam logika tetap kuat. Bahkan, sampai
sekarang, dalam studi-studi filsafat, logika Aristoteles masih selalu dijadikan
bahan rujukan dan pegangan utama.
ARISTOTELES sangat berpengaruh amat besar dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan,
seperti logika, fisika, metafisika, etika, ketatanegraandan lain-lainnya. Pengaruh
yang lebih besar adalah logika. Kalau pengaruh Aristoteles setelah zaman
Renaisans mulai berkurang,maka dalam logika tetap kuat. Bahkan, sampai
sekarang, dalam studi-studi filsafat, logika Aristoteles masih selalu dijadikan
bahan rujukan dan pegangan utama.
Aristoteles terkenal sebagai “Bapak Logika”. Akan tetapi itu bukan berarti
bahwa sebelumnya tidak ada logika, sebab setiap uraian ilmu selalu berdasarkan
logika. Logika tidak lain dari berfikir secara teratur menurut urutan yang
tepat atau berhubungan dengan sebab-akibat. Para filosof sebbelum Aristoteles
telah memepergunakan logika sebaik-baiknya. Akan tetapi Aristoteles yang
peertama sekali melahirkan cara berfikir yang teratur itu dalam satu
sitem. Artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Aristoteles memberikan
suatu uraian sistematis mengenai logika. Tidak dapat disangkal bahwa logika
Aristoteles memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah intelektual umat
manusia,
termasuk umat islam. Sampai saat ini buku rujukan dan pegangan logika
tradisional (yang harus dibedakan dengan logika modern) sebagian besar diisi
oleh logika Aristoteles.
Aristoteles membagi ilmu-imu pengetahuan atas tiga golongan, yaitu pertama,
ilmu pengetahuan praktis, yang meliputi etika dan politika. Kedua,
ilmu pengetahuan produktif, yang menyangkut pengetahuan yang sanggup
menghasilkan suatu karya (teknik dan kesenian). Ketiga, ilmu
pengetahuan teoritis, yangmencakup fisika, matematika dan “filsafat pertama”
(metafisika). Jadi dalam pembagian ini tidak ada tempat untuk logika. Sebab,
menurut Aristoteles, logika tidak termasuk ilmu pengetahuan sendiri, tetapi
mendahului ilmu pengetahuan sebagai persiapan berfikir dengan cara ilmiah,
karena itu logika Aristoteles disebut juga Organ (alat).
Logika tidak merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan, merupakan suatu alat agar
kita dapat mempraktikan ilmu pengetahuan.
Menurut Aristoteles, suatu keharusan bagi kita memiliki suatu alat sebelum
membangun sebuah angunan. Bangunan yang dimaksud adalah membina pembahasan
filosofis, sedanngkan alat adalah logika. Agar analisis filsafat menjadi
lebh tajam, kita harus memiliki logika yang andal. Jadi kekuatan dan kekuasaan
filsafat sangat bergantung kepada kemampuan logika. Bahkan, logika merupakan
tulang punggung filsafat dan subtansi metafisika, serta merupakan bingkai
filsafat. Pada gilirannya, filsafat itu tidak lebih dari penyusun
proposisi-proposisi logika yang berbentuk suatu silogisme logis.
Silogisme merupakan pokok yang paling utama dan penting dalam logika
Aristoteles. Namun, tanpa memiliki suatu pengetahuan
tentang proposisi dan konsep kita tidak akan sampai pada silogisme. Karena itu,
dalam logika Aristoteles tidak ada silogisme tanpa proposisi, sebagaimana tidak
ada proposisi tanpa konsep. Dengan demikian, unsur-unsur logika Aristoteles
terdiri atas tiga bagian. Pertama, konsep atau pengertian (Arab:tashawwur). Kedua,
proposisi atau pernyataan (Arab: qadhiyah). Dan ketiga,
silogisme atau penalaran (Arab: qiyas‘aqly).
Konsep/Defenisi
Konsep merupakan unsur dari proposisi atau keputusan. Karena itu, sebelum
kita sampai pembahasan proposisi, unsur-unsur akan diuraikan lebih dahulu.
Dalam bahasa indonesia istilah konsep diterjemahkan dengan
istilah pengertian. Istilah pengertian mempunyai arti yang lebih
luas ketimbang konsep atau tangkapan. Karena it, disini akan digunakan istilah
konsep saja yang berpadanan dengan al-tashawwur dalam bahasa Arab.
Konsep adalah suatu yang abstrak, yang dihasilkan suatu pemikiran secara
bersahaja, tanpa memberikan pernyataan yang positif atau negatif. Sebagaimana
diketahui kegiatan akal pikiran pertama sekali adalah menangkap sesuatu
sebagaimana adanya. Hal ini terjadi dengan mengerti tentang sesuatu tersebut.
Mengeerti berarti menangkapmakna sesuatu. Makna sesuatu dapat dibentuk oleh akal pikiran.
Yang dibentuk itu adalah suatu gambaran yang ideal, atau suatu ‘konsep’ tentang
sesuatu. Karena itu, konsep adalah suatu gambaran akal pikiran yang abstrak,
yang batiniah, tentang makna sesuatu.
Kalau kita hendak menunjukkannya, konsep itu harus diganti dengan lambing. Lambang
yang paling lazim ialah bahasa.Dalam logika yang dimaksud dengan “bahasa”
adalah suatu system bunyi-bunyi yang diartikulasikan dan dihasilkan dengan
dengan alat-alat bicara atau system kata-kata yang tertulissebagai lambing dari
kata-kata yang diucapkan. Jadi, di dalam bahasa, konsep itu lambangnya berupa
kata. Kata sebagai fungsi dari dari konsep disebut term. Artinya, kata-kata itu
hanya penting sebagai subjek atau prediket dalam suatu kalimat. Kalimat dalam
logika disebut proposisi. Jadi, proposisi adalah sebuah kalimat yang tersusun
dari term-term.
Proposisi
Menurut Aristoteles, proposisi adalah semacam dari kalimat. Akan tetapi
tidak semua kalimat termasuk proposisi. Proposisi adalah kalimat berita yang
menyatakan pembenaran atau penyangkalan. Karena itu proposi mengandung sifat
benar atau salah. Adapun kalimat-kalimat seperti kalimat perintah, larangan,
pertanyaan seru, harapan, keinginan, doa, sumpah, pujian, selaan dan keheranan
tidak termasuk kalimat proposi.
Proposi merupakan pernyataan tentang hubungan yang terdapat diantara dua
term, yaitu term yang diterangkan, yang disebut subjek, dan term yang
meneranngkan, yang disebut predikat. Jadi, antara subjek dan predikat selalu
ada hubungan pembenaran dan penyangkalan. Proposisi, “Ahmad adalah anak yatim”,
jika memang benar begitu, pernyataan proposisi itu benar, sebaliknya adalah
salah
Satu proposisi mengandung tiga unsure, yaitu subjek; hal yang diterangkan,
predikat;hal yang menerangkan, dan hal yang mengungkap hubungan antar subjek
dan predikatyang dinamai copula; yang dalam bahasa inggris
disebut: to be (Arab: rabithah). Pada proposisi “manusia adalah mortal”, term
“semua manusia” adalah bagian yang menjadi subjek, term
“mortal” adalah bagian yang menjadi predikat, dan “adalah” merupakan tanda yang
menyatakan hubungan antara subjek dan predikat, disebut copula
Menurut logika tradisional, proposisi pasti terdiri dari tiga unsur, yaitu
subjek, predikat dan copula. Copula mesti ada dan fungsinya menyatakan hubungan
yang terdapat antara subjek dan predikat.
Hubungan yang dinyatakan oleh copula mungkin berupa pembenaran (afirmasi),
artinya copula menyatakan bahwa antara subjek dan predikat memang sesungguhnya
terdapat suatu hubungan dan mungkin pula copula menyatakan penyangkalan,
artinya copula menyatakan bahwa antara subjek dan predikat tidak terdapat suatu
hubungan apapun.
Macam-macam Proposi
Dalam proposi, predikat dihubungkan dengan subjek. Kalau hubungan itu tanpa
bergantung kepada suatu syarat, proposinya dinamakan proposi kategoris (al-qadhiyah
al-hamliyah), misalnya, “semua manusia adalah mortal”. Kalau hubungan
antara subjek dan predikat itu berdasarka pada suatu syarat tertentu,
proposinya disebut proposi kondisional (al-qadhiyah al-syartiyah),
misalnya, bila besi dipanaskan ia akan memuai”.
Silogisme
Menurut Bertrand Russell, Aristoteles telah memberikan pengaruh yang
amat besar dalam beragai ilmu pengetahuan. Dan pengaruhnya yang
terbesar adalah dalam bidang logika, lebih khusus lagi adalah dalam bidang
silogisme (qiyas ‘aqly). Dua pembahasan terdahulu-term dan
proposisi-tidak lebih kecuali hanya sebagai pendahuluan bagi silogisme.
Sebab term dan proposisi merupakan materi bagi silogisme. Maka dalam
penilaian benar atau salahnya suatu silogisme sangat tergantung kepada
penyusunan materi-materi tersebut.
Pengertian
Inferensi (al-Istidlal)
Inferensi atau penyimpulan adalah proses mendapatkan suatu proposi yang
ditarik dari suatu proposi atau lebih. Sedangkan yang diperoleh mestilah
dibenarkan oleh proposisi atau proposi-proposi tempat menariknya. Proposi yang
diperoleh ini disebut konklusi (natijah), sedangkan proposisi atau
proposisi-proposisi tempat pengambilan konklusi disebut premis atau
premis-premis.
Ini berarti bahwa pemikiran kita berproses atau bergerak dari suatu hal ke
hal yang lain, dari satu proposi ke proposi yang lainnya, dari apa yang sudah
diketahui ke hal yang belum diketahui. Pengetahuan yang telah diketahui
merupakan panngkalan dan pengetahuan yang baru diketahui merupakan sesuatu yang
muncul dari pangkalan itu.
Aristoteles membagi inferensi kepada tiga macam:
1. Inferensi
sofistik (al-istidlal al-sofistha’i), yaitu inferensi yang berdasrkan
premis-premis yang salah.
2.
Inferensi dialektis (al-istidlal al-jadaly),
yaitu inferensi yang bersifat umum tetapi tidak mesti benar, karena ia hanya
bersifat perkiraan. Premis-premisnya
mengandunng kemungkinan benar atau salah.
3. Inferensi
demonstrative (al-istidlal al-burhany), yaitu inferensi yakin, karena ia
yerdiri atas premis-premis yang benar.
Silogisme
Sebagaimana disebut diatas bahwa silogisme adalah penemuan Aristoteles yang
terbesar dalam bidang logika, dan ia mempunyai peran sentral dalam banyak
yentang logika.
Silogisme suatu bentuk penarikan konklusinya secara deduktif tak langsung,
yang konklusinya ditarik dari premis yang disediakakan serentak. Oleh karena
itu,silogisme adalah penarikan konklusi yang sifatnya deduktif, maka
konklusinya tidak dapat mempunyai sifat yang lebih umum dari premisnya. Berbeda
dari penarikan konklusi secara langsung yang konklusinya ditarik dari satu
premis saja. Silogisme yang merupakan penarikan konklusi secara tak langsung
konklusinya ditarik dari dua premis. Contoh:
Semua manusia
adalah mortal
Sokrates adalah
manusia
Sokrates adalah
mortal
Kesimpulan yang
diambil dari contoh diatas, bahwa Socrates adalah mortal adalah sah menurut
penalaran deduktif, sebab kesimpulan itu ditarik secara logis dari dua premis
yang mendukungnya. Pertanyaannya apakah kesimpulan itu benar, maka hal ini harus dikembalikan
kepada kebenaran pppremis yang mendahuluinya. Sekitar dua premis yang mendukung
adalah benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya
benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak benar.
Referensi
Idris, S & Tabrani, Z. A. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme
dalam Konteks Pendidikan Islam. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan
Konseling, 3(1), 96-113.
Patimah, S., & Tabrani, Z. A.
(2018). Counting Methodology on
Educational Return Investment. Advanced Science Letters, 24(10),
7087-7089.
Tabrani, Z. A. (2015). Persuit
Epistemologi of Islamic Studies (Buku 2 Arah Baru Metodologi Studi Islam). Penerbit
Ombak, Yogyakarta.
Tabrani, Z. A., &
Masbur, M. (2016). Islamic Perspectives on the
Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical
Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). JURNAL EDUKASI:
Jurnal Bimbingan Konseling, 1(2), 99-112.
Tabrani. ZA. (2012). Future
Life of Islamic Education in Indonesia. International Journal of Democracy,
18(2), 271-284
Tabrani. ZA. (2013). Pengantar Metodologi Studi Islam. Banda Aceh: SCAD Independent
Tabrani. ZA. (2014). Buku Ajar Filsafat Umum. Yogyakarta:
Darussalam Publishing, kerjasama dengan Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
Tabrani. ZA. (2014). Islamic Studies dalam Pendekatan Multidisipliner (Suatu
Kajian Gradual Menuju Paradigma Global). Jurnal Ilmiah Peuradeun, 2(2), 211-234.
Tabrani.
ZA. (2015). Arah Baru Metodologi Studi
Islam. Yogyakarta: Penerbit Ombak
Warisno, A., &
Tabrani, Z. A. (2018). The Local Wisdom and Purpose of Tahlilan
Tradition. Advanced Science Letters, 24(10), 7082-7086.